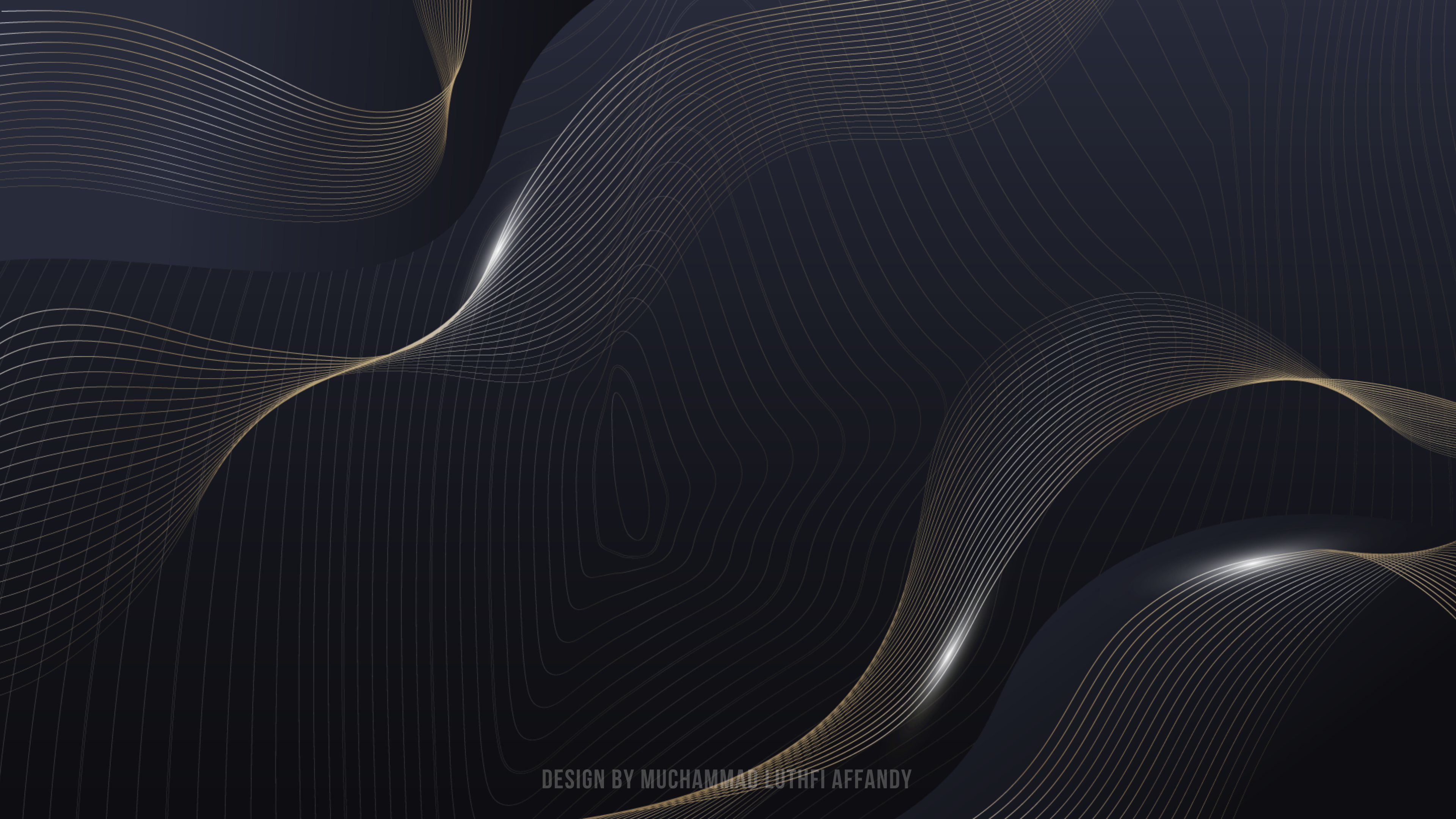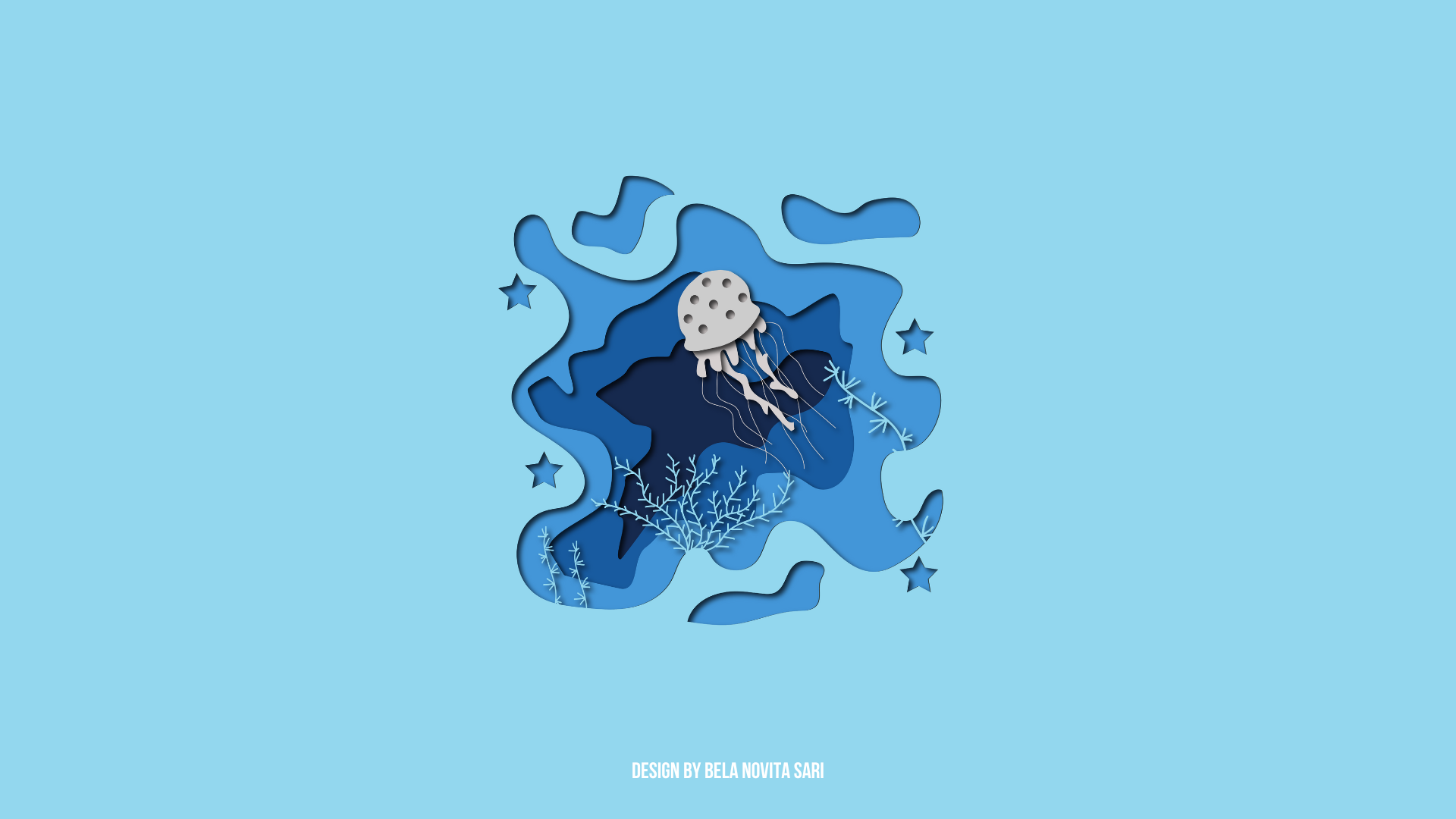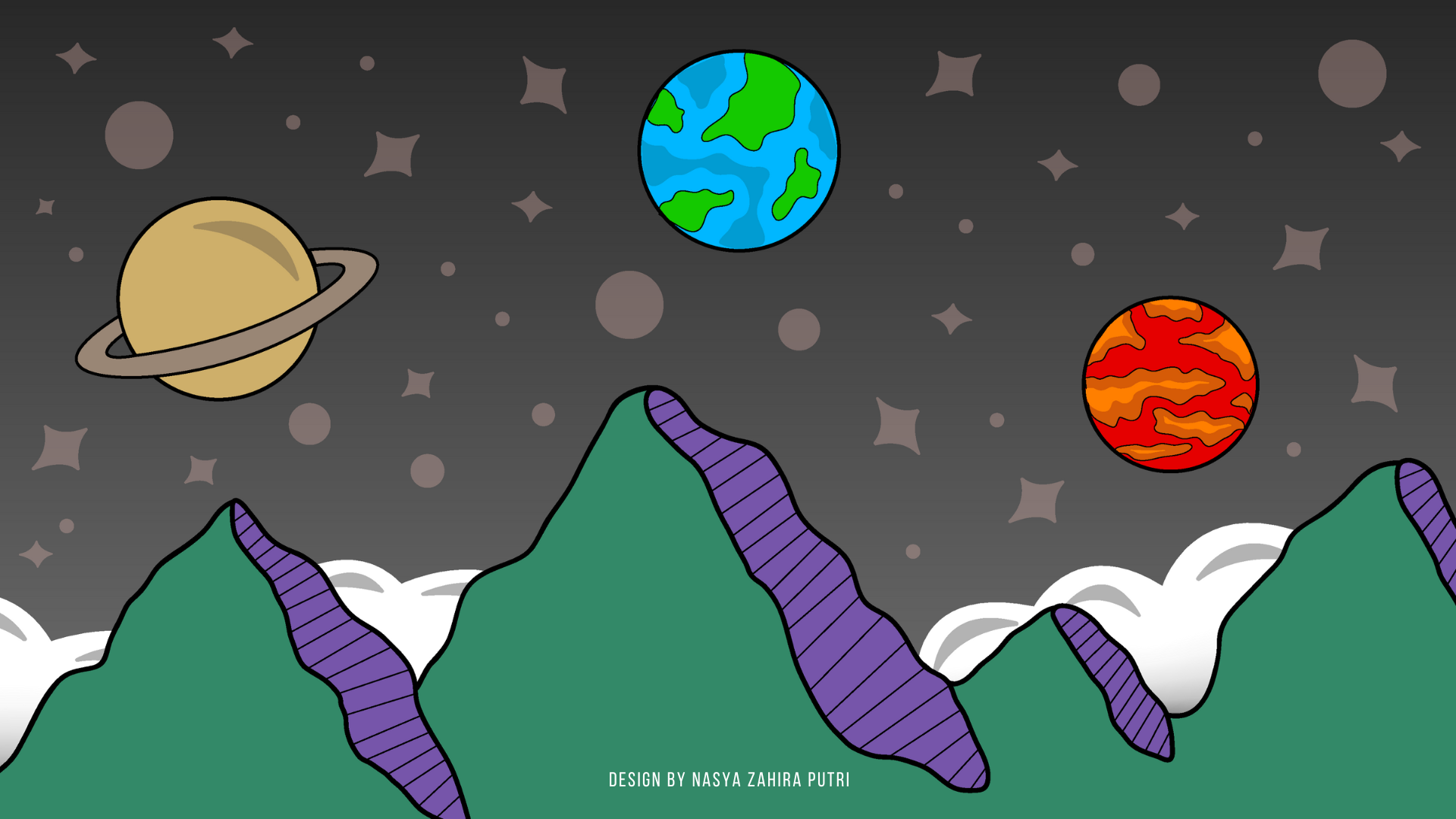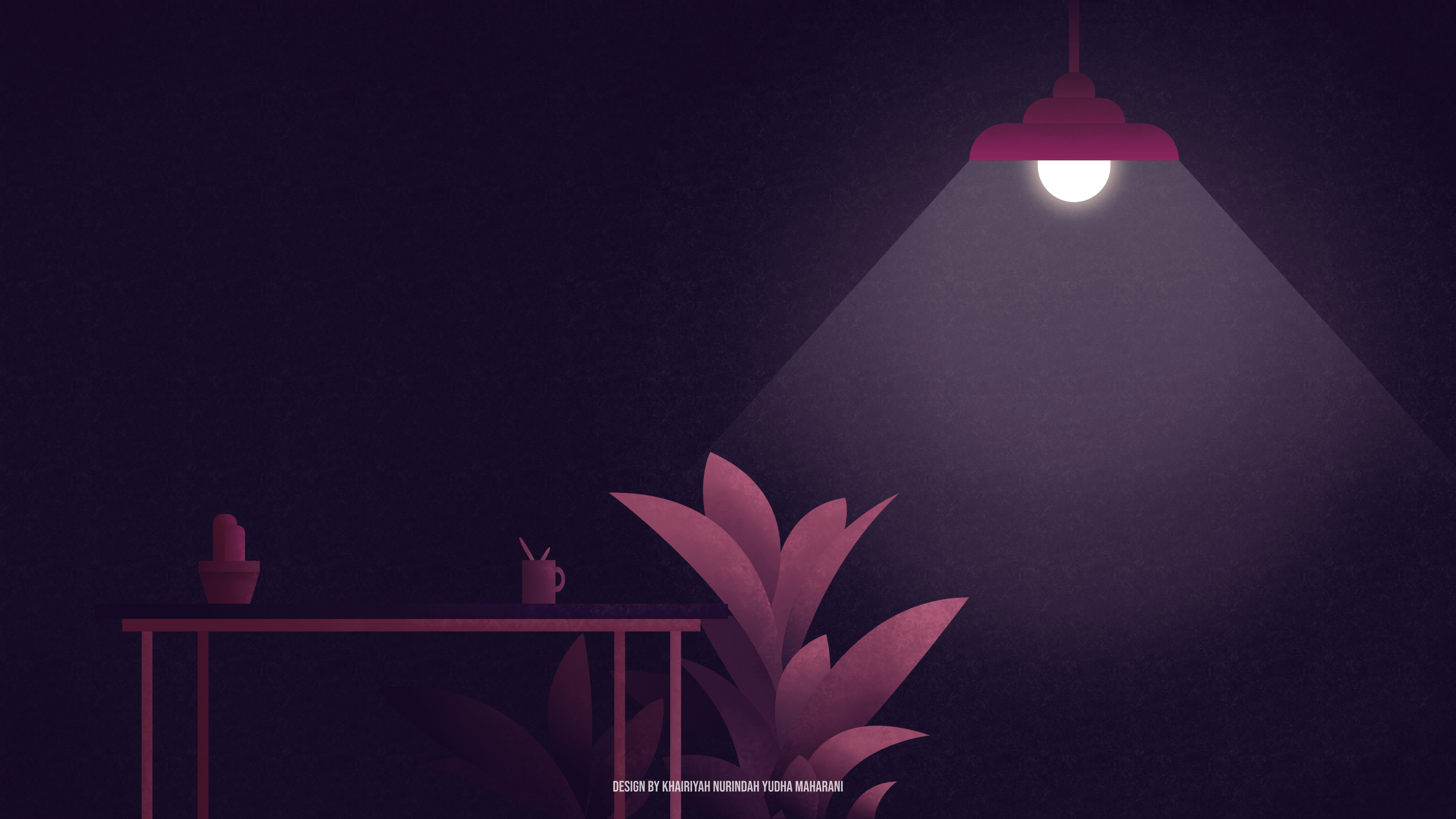Sedang aku? tidak di antara siapa-siapa
Kamu jauh berlagu menghibur dunia
Sedang aku? hanya seonggok manusia tanpa bahagia
Kamu, berdiri di antara mereka
Sedang aku? hanya berpijak di atas kakiku saja
Lagi lagi kamu, bersinar terang di bawah gemerlap sorot lampu dan kamera
Sedang aku? sinarku mati dibungkam renungan semesta
Aku dan kamu, hanya dua raga yang senjang
Lantas kita?
Apa ada ruang untuk rasa ini bersua?
Karya: Emily Azizaida Budikusuma
Mentari baru saja beranjak terbit. Kuambil sandal jepit dan dompet berisikan dua puluh ribu rupiah. Bukan dress ataupun kemeja, hanya baju tidur lusuh yang kali ini kukenakan. Kakiku perlahan melangkah, melewati jalan kecil yang agaknya tak ada satupun kendaraan bermotor yang mampu melintasinya. Dinginnya pagi memang menyegarkan, tetapi seringkali menusuk perlahan.
Langkahku terjejak pada hiruk-pikuk keramaian. Entah Bu Sari dengan sayur-sayurnya atau Pak Setyo dengan ikan asinnya yang menggiurkan. Bagiku, tempat ini bukan hanya tempat berbelanja, bukan hanya tempat mencari nafkah, melainkan juga sebuah gambaran hidup yang nyata. Tempat orang-orang berbagi kisah dan membuat cerita bersama. Masih kuingat kemarin pagi Pak Sandi membawa cerita akan anaknya yang bersikukuh ingin dibelikan tiket konser girlband ternama. Padahal, sehari-harinya hanya berjualan telur gulung. Cukup membuatku prihatin dan tersindir di saat yang bersamaan. Dan lagi, cerita Nek Minah tentang cucunya yang sakit parah cukup untuk membuat tangisku pecah di tengah perjalanan pulang.
Kulihat beberapa paman tua menikmati segelas kopi dan sepiring pisang goreng di tepian jalan. Mungkin, ini adalah tempat yang nyaman bagi mereka untuk duduk berlama-lama menikmati hiruk-pikuk dinamisnya hidup dikala fajar menyapa. Tempat terbaik bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada gerobak kayu tua yang didorong oleh tenaga harapan dan kekhawatiran. Tegar, tak terhalang bau ikan dan daging yang menyeruak, apalagi hanya sebuah genangan air dangkal yang kerap kali membawa kenangan masa kecil. Mentari saja tertunduk malu oleh kerja kerasnya yang tak kenal lelah, serta tabahnya yang tak kenal surut.
“Jadi beli tempenya, Dik?” tanya salah seorang pedagang membuyarkan lamunanku.“Jadi, bu. Totalnya berapa ya, Bu?” jawabku.
“Lima ribu saja, Dik.”
Lihatlah senyumannya yang menyejukkan. Lihat sebuah kebesaran hati dikala sepi. Rasakanlah bagaimana berbagai emosi berbagi dan tersaji di sebuah tempat yang bernama pasar pagi.
Karya: Erina Herwindalita
+ Disforia
Aku berdiri di atas traumaku sendiri
Mengira segalanya sudah selesai
Ternyata masih menyisakan benang masai
Seperti sel kanker yang tidak benar hilang dari inangnya
Lukaku pun terlanjur menjadikan hatiku sebagai induk semangnya
Luka itu terlanjur larut
Dan aku menjadi terus-menerus sengkarut
Kau tau?
Disforia ternyata seperti itu
Seperti kuku yang tumbuh di ujung jarimu
Sekalipun kau terus memangkasnya
Ia akan tumbuh keesokan harinya
Aku bertanya-tanya kapan ini berakhir
Ternyata dia harus terus-menerus diperangi sampai nadir
Kecuali kau potong tanganmu
Disforia selesai,
Kau juga selesai.
Karya: Fadila Prima Rahayu
+ Dinda
Dinda dan ia adalah kekasih lama. Lama tak jumpa, bersua, apalagi saling sapa. Dinda tak mengenalnya. Namun, ia menjanjikan masa depan dan resep awet muda. Diam-diam, ia sangat merindukan Dinda. Sayangnya Dinda berbeda. Ia sudah melupa.
Malam itu, berselimut lampu belajar, Dinda tengah mengerjakan esai yang terhenti berhari-hari. Sesekali ia bertualang di internet, mencari-cari referensi, membaca jurnal kesana kemari. Sia-sia saja. Satu, dua, tiga jam berlalu, sementara esai di layar laptop mungil itu hanya bertambah satu paragraf. Itu pun tak penuh.
Dinda mulai gusar. Siang tadi, sudah lima kali kemajuan tulisannya dipertanyakan. Dinda tidak menjawab. Ia sungguh malu untuk mengaku. Mengingat semua itu, ia sakit kepala. Dinda menarik napas panjang sembari menyandarkan punggung ke bantalan kursi. Pandangannya mengelana ke seluruh penjuru kamar, berusaha keras menggali ide, kemudian berhenti di rak buku di pojok ruangan. Dinda tertegun. Dahulu ia lancar sekali berkata-kata, tetapi sekarang?
Dinda meraih jurnal di atas rak. Jurnal usang itu berisikan konsep-konsep tulisannya semasa di sekolah menengah. Sebagian isinya masih kosong. Sebagian lagi penuh berisi tulisan. Sebuah pena tua terselip di tengah-tengahnya. Entah kapan ia meninggalkan pena di sana. Tintanya telah mengering. Tanpa berpikir lagi, ia berniat membuangnya. Tiba-tiba, pena yang ia anggap tumpul itu meneteskan tinta. Dinda terkejut. Namun bukan pena itu penyebabnya, melainkan kertas yang terkena tetesan tinta. Tinta itu terserap ke dalam kertas, lantas muncul seutas kata.
Hai, Kak,
Dinda terperanjat dari kursi. Ia pernah melihat yang seperti ini, tetapi hanya di film-film.
Saya cari-cari punya kakak, tapi tidak ada.
Kakak sudah tidak menulis lagi?
Dinda menelan ludah. Ia baca lagi pesan itu. Lagi, lagi, dan lagi. Menulis? Menulis apa yang dimaksud? Dinda pun menoleh ke arah rak buku berdebu di pojok ruangan. Isinya beraneka macam koran, majalah, hingga buku kumpulan soal yang memuat tulisan-tulisannya. Dinda sengaja mengumpulkan mereka dalam satu rak agar sempat terbaca lagi. Namun, semuanya tinggal kisah lama, sebelum kesibukan kuliah merenggut semua itu darinya.
Saya sedang sibuk kuliah. Mungkin lain waktu saya akan menulis lagi.
Dinda pun menulis di atasnya. Tulisan Dinda terserap ke dalam kertas. Ganjil dirasa. Namun, ia berusaha menelan semua itu. Sesaat kemudian pesan baru muncul.
Oh begitu. Sayang sekali.
Dinda menyeka keringat dingin. Di sela-sela keanehan itu, ia masih teringat nasib esainya. Ia kembali mengalihkan fokus sembari meyakinkan diri bahwa yang dialaminya barusan hanya bunga tidur. Namun, tak berselang lama, sederet huruf kembali muncul.
Ternyata benar Kakak bukan kawan yang baik.
Dinda tersentil. Kini tinta itu terasa mengejeknya.
Bagaimana bisa?
Dinda menunggu tinta lain muncul sembari mengetuk-ngetukkan ujung jari ke atas meja. Sayang, hingga larut malam pesan itu tak berbalas.
Tanggal bergeser. Besoknya, sepulang dari kampus, Dinda kembali menemukan sebaris kalimat muncul di atas kertas.
Kakak meninggalkannya.
Dinda meletakkan tasnya. Ia cepat-cepat meraih pena, lalu menulis di atas kertas lusuh itu.
Siapa?
Kalimat lain muncul.
Padahal ia selalu menunggu Kakak.
Dinda Kembali bertanya.
Siapa?
Pesan itu terus berkicau tanpa memedulikan pertanyaan Dinda.
Padahal ia ada dalam diri Kakak.
Dinda merasa dongkol. Ia terdiam sambil memikirkan ucapan dari tinta tersebut. Tak lama kemudian, ia mulai mengenang sesosok kawan yang dahulu ia pinang dalam kejemuan rutinitas. Sepulang sekolah atau di sela-sela kesibukan, ia selalu membersamai Dinda. Kala Dinda larut dalam bacaan, sosok itu datang, mengajaknya menari di atas kertas putih, menuntunnya menata kata hingga tercipta tulisan yang menawan. Begitu pula hari-hari berikutnya. Dinda tidak pernah merasa bosan. Sosok itu pun berjanji untuk saling bertemu saat Dinda sedang membaca buku. Dinda mengiyakan.
Namun, semenjak tulisan-tulisannya terangkat di dunia kepenulisan, hati Dinda mulai beku. Kepuasan mengalahkan orang lain membuatnya terpikat pada kompetisi. Bukan lagi kenikmatan membaca buku yang ia kejar, melainkan gemerlap hadiah yang ditawar penerbitan. Dinda tak lagi menyambut sosok itu. Ia meninggalkannya.
Seperti halnya kerajaan kuno dalam pelajaran sejarah, masa-masa keemasan Dinda perlahan surut. Memasuki bangku kuliah, Dinda mulai disibukkan dunia baru. Hadirnya bioskop dalam genggaman dan luasnya jaringan pertemanan dunia maya membuatnya tak lagi menyentuh buku. Sosok itu pun tak lagi datang. Di lain sisi, rabun kata pada Dinda nyaris sempurna.
Malam itu, barulah Dinda tersadar. Sosok inilah yang ia cari selama ini. Sosok inilah yang bisa menyelamatkan esainya. Dinda ingin sekali merengkuhnya lagi. Sayang, ia bahkan tak pernah tahu siapa namanya, di mana rumahnya, dan bagaimana memanggilnya. Dinda bertekad membaca buku lagi. Bukan sekadar baca kilat atau lompat dari satu halaman ke halaman lain. Bukan juga membaca tulisan di media sosial lantas hanyut dalam arus hiburan. Malam itu, Dinda telah mengencangkan niat. Ia mulai mengambil sebuah buku dari tasnya. Pikirannya pun khusyuk mencermati bacaan. Sementara itu, tanpa Dinda ketahui, sosok itu tengah tersenyum di belakang.
Karya: Arizqa Shafa Salsabila
Ditemani moleknya rembulan
Juga sarayu yang menusuk tulang
Senandika itu, tak kunjung usai
Beradu dengan monolog sang nokturnal
Patera dekatnya bertanya,
“Apa pemicu gelabah itu?”
Asa yang tertawan dalam imaji
Saut angin yang menguping
Berjuta ide yang bergelimang
Segudang asa dalam bayang-bayang
Lenyap, sebab sebuah keraguan
Menjadi debu, sebab tak ada aksi yang dimulai
Namun, saat insan lain di puncak,
iri hati bergejolak
sambat pun tak kunjung padam
Merutuki cara kerja semesta
Tanpa pernah berkaca
Kita memang setara, insan yang bernyawa
Kita memang sama, punya seonggok animo di kepala
Tapi, dia berjerih payah mewujudkannya
Sedangkan kau,
hanya duduk termangu.
Bersangga pada takdir dan keajaiban semata
Penganut fatalisme yang nyata
Karya: Vania Salsalbila Gusni
Hal pertama yang terpikirkan oleh orang-orang ketika menyebut nama Jakarta adalah ibu kota dengan segala kesibukannya. Gemerlapnya malam ibu kota sangat berbeda dengan kota kecilku yang berada di Pulau Sumatera. Ketika memilih Jakarta, aku berharap segala luka yang merekah akan reda sepenuhnya. Karena di Jakarta, aku mengharapkan cerita baru yang lebih indah seperti anggunnya city light yang menangkap netraku ketika pertama kali masuk ke dalam kota ini. Dalam batinku, aku berdoa, semoga ini merupakan awal yang baru bagi buku baruku.
Pagi ini adalah pagi kesekian yang harus kulalui di kota ini. Kantung mata hitam dan hati yang resah tetap menjadi temanku seolah-olah mereka juga ikut terbang bersamaku ke ibu kota.
“Kelas pagi ini dibatalkan, Ibunya lagi di perjalanan ke luar kota,” ucap salah satu teman sekelasku. Sama sepertiku, kulihat setiap mata lelah yang berusaha bangun pagi setelah bertempur dengan berbagai tugas yang menuntut untuk diselesaikan. Agar waktu tidak terbuang sia-sia, aku dan teman-teman yang lainnya berusaha memanfaatkannya untuk mengerjakan tuntutan lainnya. Dengan kepala yang berkunang-kunang, aku berusaha mendengarkan temanku yang menjelaskan tugas kelompok. Tiba-tiba, salah satu temanku meninggikan suaranya tanpa sebab yang jelas. Entah karena aku yang terlihat tidak memperhatikannya dengan baik atau dia memiliki masalah lain denganku. Pagi itu menjadi buruk dalam sekejap mata.
Hari kelima di minggu ini pun datang. Keseharian yang menyibukkan dan membosankan tetap hadir. Namun, ada yang berbeda hari ini dibandingkan hari lainnya. Hari ini aku bisa mengistirahatkan kepalaku dan melihat cinta pertamaku di Jakarta, yakni city light . Malam ini juga makin istimewa karena aku bersama seorang teman. Ya, “Sang Teman”. Tanpanya, ibu kota mungkin tidak semenarik malam ini meski lampu kota sudah gemerlap. Berbagai potret kota yang memukau tertangkap oleh lensa kameraku, salah satunya dia. Malam itu menjadi pelipur penatku setelah menghadapi berbagai masalah beberapa hari ke belakang.
Lalu, hari-hari berikutnya datang membawa berita buruk. Sekeras apapun aku berlari, ternyata belum dapat membawaku ke tempat yang terbaik. Hasil yang mengecewakan membuatku terisak di dalam hati. Terlalu menyedihkan menurutku jika harus menangisinya di depan semua orang. Akhirnya, rasa kecewa kubawa di dalam kamarku yang berwarna biru-abu. Namun, aku memperingatkan kepada diriku sendiri bahwa hari ini bukan saatnya jatuh. Pada hari berikutnya, aku berusaha berlari lebih keras lagi walaupun aku mengetahui fakta aku akan terjatuh. Dan ternyata benar, aku memang terjatuh dan lebih keras. Di tengah perjalanan yang penuh luka, akhirnya aku menangis lebih keras di dalam diam ketika menemukan “Sang Teman” bersama yang lain. Dan ku ingatkan sekali lagi pada diriku, ini bukan saatnya jatuh.
Layaknya daun yang jatuh di musim gugur, mereka yang lain datang memelukku. Benar, mereka adalah sahabatku. Pada buku ini, aku lupa menceritakan bagian terbaiknya selain tentang city light . Pelukan yang sehangat mentari pagi membuatku kembali bergelora walaupun aku akan jatuh lagi. Walaupun aku meminta pelukan itu berkali-kali, itulah bagian terbaiknya. Hangatnya memberikan kesempatan padaku untuk membuka pintu-pintu baru yang ada di kota ini. Berkatnya, keberanian dan tekad muncul dari lubuk hatiku yang terbelenggu.
Buku tentang Jakarta masih sama dengan buku lainnya. Layaknya city light yang hanya muncul saat malam, semuanya sendiri punya waktu dan tempatnya. Suka dan duka hanya bersifat sementara hingga datang pelipurnya. Buku di kotaku juga memiliki tempatnya juga dalam cerita hidupku. Buku tentang Jakarta bukan kisah baru, melainkan kelanjutan kisah mengenai seorang anak manusia yang terus tumbuh walaupun di tempat yang baru.
Karya: Nabila Randrika Putri
Buku kecil dan tulisan warna biru
Tahu betul isi kepala yang tak bisa jauh dari bayang semu
Menyimpan segala cerita-cerita sendu
Jua hiruk-pikuk serpihan memori lalu
Lagi-lagi rupanya,
seonggok memori lalu
Tiada henti temani kesunyian jiwa-jiwa sedu
Runtuhan ego memekikkan akal pikiran
Terbesit kalimat yang sering terngiang
Andai dulu tak jatuh dalam buainya!
Lekat erat kenangan pada pemiliknya, ujar semesta
Bisikkan, bagaimana cara hilangkan belenggu sesal?
Deru alir sesal mengarungi sanubari diri
Menyisiri tiap bulir-bulir album nestapa
Karya: Karina Cindy Rahmanto
Tatapanku kian lekat, menatap foto hitam putih dalam genggaman tangan. Tak seperti suasana kamar yang hening, benakku terlampau riuh hingga tak mampu lagi untuk kubiarkan. Sesak bergumul di dada. Pelupuk mataku basah oleh air mata. Kutenangkan diriku. Kukatakan tak apa perihal yang berlalu. Namun, tangisku pecah. Ingatanku melayang pada kejadian empat tahun lalu, tepat pada tanggal yang tertera dalam foto hitam putih itu.
***
Malam itu, aku mendapat pesan yang berisi ajakan untuk bertemu. Pengirim pesan itu ingin berkeliling Kota Jogja bersamaku. Aku pun mengiyakan. Selain tidak ada jadwal kuliah, tidak baik rasanya jika aku terus-menerus menghindar setiap ia ingin bertemu.
Keesokan harinya, ia datang ke indekosku yang berada di dekat TVRI Jogja. Ia datang dengan motor tua kesayangannya, motor Shogun warna merah. Ia berhenti di depan gerbang indekosku. Aku yang melihatnya pun lantas beranjak dari kursi depan kamar. Senyumnya yang mengembang semakin terlihat jelas ketika aku sudah berada tepat di samping motornya. Aku bimbang. Aku harus apa. Apakah aku harus mencium tangannya yang menua? Sudah berapa lama aku tak melakukan itu?
Tampaknya ia tahu jika aku canggung dan bingung. Ia lantas memecah kecanggungan itu, bertanya bagaimana kabarku sembari menyerahkan helm. Aku pun menjawab bahwa aku baik-baik saja tanpa bertanya balik kepadanya. Ia pun terlihat tak apa dan mempersilakanku naik ke motornya.
Tujuan pertama kami adalah Malioboro. Katanya, ia sudah lama tidak berkunjung ke tempat ini. Aku sendiri sudah hampir tiga tahun di Jogja, tentu Malioboro tidak lagi asing untukku. Akan tetapi, tak apa, ini akan menjadi cerita pertamaku berkunjung ke Malioboro bersamanya. Selama berkeliling Malioboro, ia terus bercerita, dari pengalamannya pertama kali ke Malioboro hingga bagaimana hari-harinya saat ini. Sesekali, ia bertanya padaku, tentang bagaimana kuliahku, apa kabar ibu dan saudaraku di Surabaya, serta kapan kakak perempuanku akan menikah. Katanya, ia ingin menjabat tangan penghulu, menikahkan kakakku.
Aku yang awalnya canggung, akhirnya bisa bersikap biasa saja. Aku menimpali setiap ceritanya tanpa rasa ragu dan bimbang. Cerita kami berdua terus terdengar di antara bisingnya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang. Rasanya, hari itu berjalan begitu lambat, seolah Sang Pemilik Kehidupan memintaku untuk rehat dan menikmati hari itu dengan baik.
Menjelang sore, ia mengajakku ke pantai untuk menikmati senja. Lagi-lagi, kami berbagi cerita, ditemani awan yang berarak mengiringi matahari kembali ke peraduan. Tiba-tiba suasana menjadi hening, kami terdiam, memandang jauh ke laut yang tenang.
“Ndi?”Merasa terpanggil, aku pun menoleh dan bertanya, “Ya, Pak?”
Ia terlihat mengembuskan napas sebelum bicara. “Bapak minta maaf ya, Ndi, kalau selama ini belum bisa jadi Bapak yang baik buat Nindi.” Ia menoleh ke arahku, “Bapak minta maaf buat Nindi kecewa karena memilih bercerai dengan Ibu, maaf, Bapak nggak bisa nepatin janji Bapak sama Nindi. Bapak minta maaf ya, Ndi?”
Aku melihat kesungguhan di balik tatapan matanya. Senyumnya pun tampak tulus. Dengan jarak sedekat ini, aku tertegun melihatnya. Aku baru melihat gurat kerutan di sekitar matanya, satu dua helai rambutnya pun nampak sudah memutih. Ternyata, ia sudah semakin tua. Kemana saja aku selama ini hingga baru menyadarinya. Aku pun memeluknya dengan isak tangis yang kutahan. “Iya, Pak. Nindi sudah memaafkan, Bapak. Nindi juga minta maaf sama Bapak, selama ini Nindi tidak pernah memberi kabar. Maaf kalau sikap Nindi buat Bapak jadi merasa bersalah. Bapak tidak salah, kok, Bapak selalu jadi Bapak terbaik buat Nindi.”
***
Hari itu rasanya lega sekali. Dapat kembali berhubungan baik dengan orang hebat yang pernah kutemui di hidup ini, Bapak. Aku memang pernah membencinya. Akan tetapi, satu yang kutahu, sudut pandang yang berbeda membuat ceritanya pun menjadi berbeda. Itulah yang terjadi pada Bapak dan Ibu. Aku yang saat itu tak paham akan kejadian sebenarnya, hanya menerima dan turut menyalahkannya. Padahal, ia tak sepenuhnya bersalah.
Namun, aku bersyukur, Tuhan masih memberiku kesempatan untuk meminta maaf dan bercerita dengannya sebelum ia kembali ke sisi-Nya. Hari itu memang hari terakhir aku bertemu dengannya. Dua hari setelah pertemuan itu, Bapak masuk rumah sakit. Ia terkena serangan jantung. Sekali lagi, aku menyesal tak mengetahui apa yang ia lalui selama dua tahun terakhir. Ia berjuang seorang diri untuk mengobati penyakitnya. Sesal tak lagi berarti. Akan tetapi, pelajaran setelahnya menjadi amat berarti bagiku.
Karya: Aghnia Amalia
+ Mutiara
“Mencari susah, tak memiliki pun susah. Sudah berulang kali ditegaskan, tetapi tetap acuh.”
Dalam dekapan lara
Semesta enggan menaruh kesaksian wicara
Ruang lagi masa tak kenal arah bermuara
Tak pandai diungkap, nurani turut bergelora
Membumihanguskan kemurnian telaga jua menara
Sudah tak berdaya pengelana mutiara
Lemah, hidup pun tak berselera
Terjebak ganasnya lilitan berwujud mantra,
terperangkap antara rimba belantara,
lagi terjerumus pusaran afeksi tiada tara
Oh, rasanya nian indah dan mesra
Menyelisik ke ujung butala Halmahera
Sekadar harapkan sejumput kemurnian mutiara
Perasaan berdegup beralunan bisikan suara
Bersandarkan merdunya lantunan aura
Namun, bukan berlagukan orkestra
Hanya pekat tertuang pada hamparan sastra
Beralaskan kelamnya tinta asa di tiap untaian aksara
Sebagai pembuka kisah yang sekadar metafora
Mulanya terasa pahit berseri
Hingga tenggat perih sanubari menghampiri
Merasakan segenap larik demi larik nyali mengalir dalam derasnya arteri
Menusuk, semerbak wangi minyak kasturi
Seraya menari dan mengitari mentari
Mustahil untuk dihindari
Bahana kasih akhirnya terlahir kembali
Bukti autentik kuasa Almalik yang tak mampu ditimpali
Ibarat garis hidup yang terombak serupa anomali
Sekaligus mencampakkan kenormalan yang memonopoli
Oh, sungguh syukur terpanjat berkali-kali
Kini, pengelana tak perlu mengaguminya sesekali
Sebab mutiara sudah di tangan yang ahli
Sosok punggawa hati bertajuk kasih telah mengungguli
Riuh gemintang bertabur kepermaian temali
Menyimpul erat, penuh kendali
Kisah terpahat begitu kuat berbalut corak artefak
Terlukis jamak seiring mutiara menapak
Kendatipun dirasa terlampau acak dan abstrak,
disesaki delusi bayangan dalam benak,
lalu dihantam derau yang lasak
Daksa kerap kali bersemarak jua bergejolak
Seakan ingin memaksakan kehendak
Cakapkah pengelana menghalau penambak asing?
Tangguh menjaganya dengan lengan baju tersingsing
Tahan banting dalam situasi penuh genting
Demi bersua lantas selamanya bersanding
Sekalipun skizofrenia ikut mengiring
Seketika terdengar sayup-sayup melodi seruling
Lirih hingga berapi-api, terus berdering
Menggugah raga yang tengah berbaring
Mata berkedip dan bekerling
Sembari menarik napas panjang satu ketukan di malam hening
Oh, lagi-lagi kepingan bunga tidur yang menguning
“Kepingan terus berjatuhan menitik. Entah tafsir dari mana yang mengatakan perihal autentik. Sampai abnormalitas tak merasa berbeda dan terasa menggelitik.”
Karya: Muhammad Almas Yafi'
Sadari ada yang mesti diperbaiki.
Berhenti sejenak.
Oasis muncrat ketika aku tersesat.
Keluarlah! Ke arah sana!
Dimana harusnya debu berkumpul dengan batu.
Agaknya mulai banyak manusia lupa asalnya.
Matanya buta,
tertipu perigi yang katanya sangat dipuja,
naas, memantulkan wajahnya saja tak kuasa.
Telinganya tuli,
terpekik jeritan di sudut ibukota.
Nampaknya jiwa yang kehilangan bayangan itu menabrak cermin.
Terserak!
Karya : Siti Nur Wulan Sha Bana
Termenung dengan bola mata yang terus bekerja melirik ke sana kemari melihat gerak-gerik manusia-manusia yang penuh semangat dengan raut wajah ceria menyambut hari. Seakan semua terlihat bahagia tanpa keluh kesa sedikit pun dengan langkah kaki tak serentak sambil sesekali tersenyum bahagia membuat orang-orang seperti dia iri melihatnya.
Dengan wajah lesu hari ini dimulai. Sudah hampir 5 jam ia duduk di taman kota dekat kompleks rumahnya dengan penyuara telinga yang bertengger. Sudah 5 jam pula belum dia temukan orang yang sekiranya mirip dengan nasibnya yang tinggal menunggu kapan antrean kesialan selanjutnya datang lagi. Hampir lelah kornea menari-nari, akhirnya dia melihatnya. Wanita paruh baya dengan keringat mengucur deras sedang bekerja dengan semangat walaupun satu tangannya sudah tak berfungsi lagi. Namun, semuanya seakan tertutup oleh hasrat dalam menjalankan hidup dengan penuh rasa syukur.
Hatinya terketuk, bukan sekali tapi berkali-kali. Ternyata masih ada insan seperti itu di semesta ini. Hatinya memberontak tak bisa ditenangkan lagi. Seakan tertawa dan menyampaikan betapa menyedihkan hidup menjadi dirinya yang sekarang. Bodohnya, sudah sekian tahun lamanya bola matanya hanya melihat orang-orang yang menampakkan mimik bahagia di atas kesempurnaan yang dimiliki. Tanpa sadar wanita paruh baya itu telah hilang dari pandangan. Dan di sinilah lamunannya bermula.
Sedih dan bahagia waktu tak akan berhenti. Semesta tak akan prihatin. Alam tak akan menangis hanya karena dirinya. Menyelusuri dunia ternyata seasyik ini. Jangankan tertawa sampai sulit bernapas, menangis pun bisa demikian. Yang dia mau? Yang dia cari? Ada di sekitarnya. Namun, mungkin berada sedikit di bawah dari target yang terpatok kokoh. Dengan hebatnya, manusia sombong ini rela mati-matian mengejar sedikit itu padahal artinya tak terlalu banyak. Satu titik telah ditemukan. Satu jalan telah terbuka. Satu tujuan sudah menyapa. Hingga akhirnya dia tersadar bahwa semua akan berseri dikala disapa dan dikala waktu pas untuknya ada karena hidup tak selamanya di atas yang artinya hidup juga tak selamanya di bawah.
Drrrtt... Suara telepon genggam menghentikan lamunannya. Dengan semangat ia berdiri sambil menjinjing tas jinjingnya menuju tempat masa depannya bertaruh.
“Level baru dimulai,” katanya sembari pergi meninggalkan taman kota.
Karya : Nurul Adhilah Busmah
Jarum jam menunjuk arah timur laut di tengah malam yang sunyi dan aku masih terjaga. Entah mengapa tiba-tiba sekali dan tanpa sebab aku mengkhawatirkan langkahku di hari esok. Akankah besok kaki ini masih bisa menapak dan berjalan? Akankah kaki ini hanya bisa terlentang di atas kasur dengan tidak berdaya? Ataukah ia akan berlari mengejar apa yang seharusnya ia kejar? Bimbang sekali rasanya menyadari bahwa jarum jam terus berdetak dan aku bahkan tidak tahu mengapa aku bernapas hari ini. Parahnya lagi, otak ini seakan telah didoktrin bahwa besok akan lebih menyeramkan dari hari ini. Tanpa sadar sungai kecil mulai terbentuk di pipi.
Aku punya harapan yang tinggi. Aku punya mimpi yang harus diperjuangkan. Aku punya cita-cita yang harus diraih. Namun duniaku saat ini seakan enggan menunjukkan jalan mana yang harus kutapaki menuju ke sana. Aku tenggelam dalam dilema, sedang mimpi-mimpi itu terus melintas di kepala dan terkadang menjadi sebuah film pendek yang kutonton dalam pikiran. Kisahnya semakin mantap saja. Tetapi aku masih di titik yang sama.
Tiba-tiba aku berhenti sejenak. Sebuah kalimat dibisikkan ke telinga kananku.
"Memang tak akan ada habisnya jika hanya kau pikirkan."
Entah dari siapa tetapi sungguh tajam menusuk hati. Isi kepalaku mulai berubah. Baru saja aku ditampar hingga tersadar. Semangatku mulai berkobar merubuhkan semua dinding kebimbangan yang telah lama kubangun. Aku diberi petunjuk.
Mungkin dunia tampak membingungkan. Tetapi jika aku tak berani mencoba melangkah ke salah satu arah, aku tidak akan menemukan jawaban. Nyaliku terkumpul penuh untuk menjadikan tamparan malam itu tidak sia-sia kuterima. Perlahan kutapaki satu per satu jalan-jalan itu. Ketika buntu yang kutemui, berbalik arah dan mencoba jalan lain adalah kewajiban. Memang tidak semudah itu untuk memulai langkah dari awal. Marah, kecewa, dan lelah menjadi atmosfer perjuanganku. Tetapi bayang-bayang mimpi merupakan penyulut api semangat terbaik. Meski setelah mencoba melangkah mimpi-mimpi itu kadang terasa menjauh dan kadang terasa sangat dekat. Demikian berulang hingga habis jatah gagalku.
Hingga suatu saat, aku menemukan jalan yang benar dengan kaki yang sudah hampir putus rasanya, hati yang sudah hampir menyerah, dan pikiran yang seakan sudah menjauh dari mimpiku. Terbayar semua air mata yang mengalir, keringat yang menetes dan hati yang teriris. Rasa puas berkibar dalam diri. Hingga aku kembali tersadar, aku baru saja membangun dunia baru dengan banyak jalan baru yang harus ditapaki.
Karya : Gloria Stephany H. C.
Aria memetik gitar di pangkuan. Lepas semester gasal ia lalui di ranah rantau. Sudut-sudut kampus sepi. Instrumen berdebu. Studio tak bernyawa.
Di luar, lembayung sore menjelma keunguan. Aria menghempaskan gitarnya kasar. Sial! Semakin lama, hasrat untuk pulang justru kian menyiksa. Ia melangkah keluar, demi berdiri di tepi ruang terbuka lantai tujuh.
Hiruk pikuk kota menjelang senja terbentang di ujung kaki. Lampu rumah-rumah petak yang enggan berdiri hingga barisan gedung pencakar langit yang tegak berkuasa mulai menyala satu per satu layaknya rangkaian kembang api. Bekerlap-kerlip. Derum kendaraan ramai di jalan besar beraspal mengantar setiap insan pekerja kembali ke peraduan. Semua tergesa, ingin lekas bersua dengan keluarga.
Jemarinya mengetuk-ngetuk pagar pembatas. Memainkan melodi yang dulu sang ibu lantunkan tiap senja sambil memangku tubuh kecilnya di pekarangan. Ia akan duduk mendengarkan, tangan mungilnya menggenggam erat selempang sang ibu, berjuang agar tak lelap sebelum santap malam. Embusan angin mengiringi nada demi nada. Perlahan, melodi mulai terdengar macam elegi. Meringkus asa dalam dada, sesak dihantam sesal.
Senandung sang ibu berakhir. Biasanya, ia akan menepuk kepala anaknya dua kali, lalu beranjak ke dapur. Sementara sang anak memandang takjub guratan malam berhias konstelasi gemintang kala berorkestra. Tapi tidak. Kedua mata sang ibu terpejam. Tenang, amat tenang. Aria diam di pangkuannya, meremas selempang sang ibu lebih erat. Ia tahu. Tak sedetik pun ia akan mendengar melodi sang ibu kembali.
Sendiri membuat Aria sadar. Lari ke ibu kota gagal membuatnya lupa akan lara.
“Aria.”
Sontak Aria menoleh. Ia bersumpah bahwa tak ada seorang pun bersamanya. Tapi nyatanya, wanita itu berdiri tepat di sana. Aria mundur selangkah, diam memperhatikan. Wanita itu tampak lebih muda dari yang seharusnya. Gaun dan sepatu sewarna kayu willow nampak tak asing. Selempang tergantung di kedua siku. Berkibar disapu angin. Halus, amat halus. Ia tersenyum, menatap teduh.
“Kau bisa ikut sekarang, Nak.”
Tangannya terulur lembut. Damai terpancar. Meyakinkan Aria untuk turut serta.
Aria tertegun. Ia ingin kembali. Ia seharusnya tak bisa kembali. Tapi mengapa wanita itu ada di sini? Dengan mudahnya mengajak Aria pergi?
Aria kembali menatap kota di bawah kakinya. Bertanya-tanya.
Tunggu. Masih banyak yang belum usai. Sekolah, panggung, konser impian, bahkan demi kembali melewatkan malam sarat gelak tawa bersama kawan, belum tercapai. Bagaimana dengan rekaman yang baru setengah jalan? Bagaimana dengan rencana tampil di festival bulan depan? Belum! Belum waktunya untuk pergi!
Di balik punggung, wanita itu mengangguk. Mengisyaratkan bahwa mereka tak punya banyak waktu. Pekat sekejap. Dengung bergema di dua sisi.
“Tuhan! Aku bisa kembali pada ibu! Aku bisa mendengarnya lagi!”
Ragu, Aria meraih uluran tangan sang wanita. Tubuhnya ingkar atas logika. Namun, sesal itu sekejap sirna. Pupus terhempas angan baru. Angan yang ia rindu.
Aria terpaku pada mentari yang surut di ufuk barat terakhir kali, sebelum beralih menatap rupa kirana sosok yang digenggamnya. Ia tahu. Pergi adalah niscaya. Hanya terlambat sadar, waktunya tinggal di jagat fana sesingkat percik kembang api.
“Kita pulang.”
Karya : Marini Safa Aziza
Dari bilik pintu aku mendongak meraih pandang menuju sudut-sudut ruang. Menerka rupa di mana sedang kamu bersemayam, apa sibukmu yang sedang di bibir pengharapan. Carut-marut dadaku dihendaki kenyataan, menilikmu beradu tatap dengan puan semampai berbalut hanfu.
Uar amor membaur sebau kenangan basah. Kau musti ingat gemerisik kala itu membubuhi tawa ditengah Kali Angke tempatmu bercerita perihal haru biru. Ada yang meredam hangat melebihi marmer mujur tempatmu menaruh dupa. Semburat jingga berjejak Burung Gereja sore itu naas turut hangat dalam dada. Jemari saling mengisi meski gamang kerap memberatkan hati. Sore itu ia telah meluruh, menguap mengudara menjadi talkin panjang soal kehidupan.
Bersumpah sekarang bahwa tak pernah dikultuskan namaku. Berbisik semburat guyub menyerta-serta dersik, susutnya Daun Murbei kini telentang di atas tanah. Adakah pernah angin mati mengumandangankan kasih paras Venus dan Mars? Adakah pernah hujan tajam memahat kisah ruang Bhrams dan Clara? Mulutmu komat-kamit bak merapal mantra, sedang aku diam memandangi teduh phobos deimos melingkari hitam bola mata. Kini keduanya mengelilingi wanita satu depa dihadapanmu. Senyumku terbit sebentar sebelum akhirnya dada merisak tangis, sebagai perwujudan mampu melihatmu melakukan Tea Pai dengan khidmat.
Kamu banyak mengungkit soal puisi cinta Kahlil Gibran, kini aku khatam rasanya. Hikayat panjang bertumpuk hasil suhad tak karuan sejak kau putuskan untuk berhenti melanjutkan perihal kita. Bedanya, ia kepalang dingin untuk dikatakakan pula disampaikan. Muaranya, aku hanya mengumpat kasar pada pasir dalam gelas waktu, memaki mengapa tak bisa hidup selamanya dimasa lepas tawamu disauti azan magrib kala itu.
Tudungku berhembus melambai tak karuan merayakan pertemuan. Mengapa kita seperti bulan bersat siang hari? Selindung diantara alufiru dunia, acuh menunda-nunda perpisahan menyemarakkan ketidakpastian. Mengapa buta menjadi pilihan untuk sebuah buruk melintang? Dirimu bertandang kemudian pamitan berjarak satu pejaman. Seperti elegi berulang-ulang, tidakkah umuk inginku soal tudungku dan dupamu menggenggam kata selamanya?
Berakar pujangga merotan lara, tabuhan gerendang jiwa semoga tidak membangunkan kamu yang berjarak satu hasta dimuka badan. Tangan terulur menggapai, berjinjit usaha melangkahi batas diri. Landai tercerai-berai, kanan-kiri, mundur satu-satu meski belum sempat dituai.
Karya : Khansa Luthfiyah Deva
+ Begini
Begini,
Telah kau cintai dirimu hari ini?
Telah kau ucap syukur atas kecupan Sang Pemilik Galaksi?
Telah kau beri waktu bagi sesama penghuni bumi?
Begini,
Sisihkan waktu untuk bersua dengan diri
Tanyakan, apakah dia sudah cukup baik di tengah tuntutan duniawi
Lihat, sudahkah dia mengucap selamat pagi pada kerabat dan famili
Amati, ketukan yang dilantunkan oleh langkah kaki
Apakah dia semakin jauh dari tujuan utamanya di bumi?
Lalu kau bertanya, kenapa harus begini?
Karena dengan begini,
Dirimu adalah manusia
Salah, mengalir dalam darah
Serakah, selalu ingin menyapa
Sakit dan amarah, bagian yang utama
Ego, menjadi tantangan di setiap ketukan masa
Kuasa, hal yg kau kejar hingga terpatah-patah
Sering kau lupa, apa yang jiwamu butuh sebenarnya
Sering kau lupa, sehingga menyakiti batin dan rupa
Sering kau lupa, bahwa sesama tak bisa kau tuntut sempurna
Sering kau lupa, banyak jiwa yang menyayangimu tanpa ‘jika’, tapi tak kau pedulikan dengan alasan sebuah ‘hanya’
Terlalu sering kau lupa bahwa kau tidak hidup di alam kekal, melainkan berpijak di tempat singgah sementara
Ketika ku tanya, kau jawab dunia yang membuatmu jadi begini
Membuatmu terus mengejar tanpa henti
Kau keluhkan kalau dunia ini penuh duri
Tapi, memang benar, dunia seperti ini
Tempat ini dirancang untuk mematahkan banyak mimpi
Tempat ini ditakdirkan menjadi poros penghancur hati
Tempat ini dibuat untuk membuatmu sedih dan berteriak perih
Tetapi, coba lihat dari lain sisi
Berapa banyak petaka, yang sebenarnya kau hindari dari mimpi yang tak jadi bunyi
Berapa banyak insan dengan hati bersih, yang kau temui karna patah di tengah persimpangan jalan sebelum ini
Berapa banyak bahagia yang muncul setelah diri ditebas oleh tangis yang menggerogoti
Lalu kau tanya lagi, bagaimana kalau sudah begini? Bagaimana kalau sudah seperti ini?
Sekali lagi kujawab begini,
Tuhan baik, kau saja yang selalu berburuk pikir
Sang pemilik bumi tahu siapa yang Ia pilih
Bukan sembarang pati, tapi bibit penakluk bumi
Dia ciptakan semesta, untuk si fana yang mumpuni
Dia beri kesempatan bagimu untuk berkontribusi bukan kerja bagai budak priyayi
Karna begini, karna sudah seperti ini,
Dia hadiahkan kau manusia yang mencintai dan kau cinta
Di perjalanan ini, mereka tempatmu berbagi
Jangan sampai lupa, jangan nanti ketika sepi kau salahkan insan lain
Karna begini, karena sudah seperti ini, jangan seenak kepalamu menyakiti diri
Itu juga milik-Nya, kau jaga dan kau kasihi
Karna dia, teman sejati yang kau cari
Dengannya, kau hidup hingga liang lahat jadi tempat singgah terakhir.
Karena begini,
Penting membuat dirimu merasa tenang di tengah bisik arus ramai
Penting untuk memupuknya menjadi jiwa damai abadi dalam raga yang habis di makan jarum detik, agar tidak menyusahkan ketika dia melambai pergi
Penting bagimu merawatnya, membuatnya bahagia, dan menjadikannya baik di mata Sang Khalik.
Jika kau merasa embun pagi sudah tak bisa menenangkanmu lagi, kupersilakan kau untuk duduk di sini. Mungkin kita butuh sedikit bincang.
Aku tahu kau pernah menyelam jauh ke dalam relung hati. Lantas kau merasa seakan-akan jiwamu berontak, ia sekarat.
Hidup yang kau tatih kini hampir temaram.
Pekan terasa bukan lagi tujuh, melainkan keluh.
Mungkin, ini sudah saatnya kau melihat teman lama.
Kudengar, ia sudah rindu akan sua.
Kau kembali menatap cermin kelabu itu, sambil tersenyum dan menyadari bahwa teman lamamu adalah dirimu sendiri.
Diri yang kerap kau hakimi, seakan tak ada pendosa seapik engkau.
Sayang, kutahu ia butuh didengarkan.
Ragamu haus akan tenang, ia mengulum tawa, sedang sukmamu menyumpah jemu.
Lamun kau membekamnya lagi, menyimpannya ke dalam kulit-kulit, dan kembali berhipokrit.
Di sudut ibukota, di bawah kentara lampu jalan yang mulai redup, ditambah hiasan binar bulan yang serempak menjadi kelam, aku duduk. Dengan jiwa ringkih dan badan yang merunduk, sembari menilik gerombolan bola kecil yang memantul di dinding bebatuan. Ku hitung, jumlahnya dari satu sampai puluhan ribu.
Demi Tuhan, sampai detik ini hatiku tetap tak terima. Dengan mata sembap, aku menatap rintikan itu penuh dengan dendam, seakan hujan adalah sesuatu yang kejam.
Aku ingat detail nadamu saat kau bilang bahwa hujan adalah hal yang menyenangkan. Kau bilang bahwa dia selalu datang dengan tujuan yang mungkin orang lain tak pernah menyadari. Entah untuk menolong anak akar yang hampir mati kekeringan, atau memberi minum pada hijau yang sekarat karena kehausan.
Tanganku beku dan mulai mati rasa. Kini yang kudengar bukan lagi nada tinggimu , melainkan suara geraham yang saling beradu tak mau kalah. Rembesan hujan menjalar pada tiap sela sepatuku, membuat jemari kaki turut gemetar.
Tiap titiknya seakan menandu pada incian memoriku, tentang dia yang hilang ditelan hujan. Sejak hari itu, hujan yang menyenangkan sudah usang.
Belum genap sebulan, tepatnya 27 hari yang lalu. Hari itu Rabu, di mana aku mengenal sesosok nama baru. "Dirgantara," ucapmu dengan tutur lantang dan vokal yang jelas. "Jingga," balasku sembari menyambut asungan tanganmu. Sontak dengan agak ketus kau bilang aku punya nama yang tak biasa. Bising hujan menyoraki kita, dua anak manusia yang tanpa sengaja bertemu dalam roman kuyup dan bentuk tak karuan.
Rupanya kau benar. Hari itu hujan diperintah Tuhan untuk menautkan kita pada sebuah pertemuan. Di emperan swalayan itu, kau membongkar isi tas punggungmu yang berisikan sebuah payung. Kau beberkan payung berukuran besar, yang awalnya kukira sebuah tenda. Selangkah kau keluar dari muka pertokoan itu, kau menawarkan diri untuk mengantarku pulang. Kau memang gila! Entah di mana akal sehatmu. Kita adalah dua orang asing yang baru saja bertemu, jelas aku menolak.
Tak lama, kau bersila di bawah lingkar payung yang kusebut tenda. Satu per satu kucuran air, terjun dari helai rambut lancipmu. Ternyata, kita juga punya sebuah keserasian, sama-sama tak suka kesenyapan. Kau banyak bercakap, sedangkan aku banyak menyaut. Kau sangat paham tentang benda yang turun dari antariksa biru di atas sana. Kau bilang bahwa hujan merupakan utusan Tuhan dalam menyampaikan setiap pesan.
"Apa namamu punya arti?" tanyaku tanpa menoleh padamu sedikit pun. Katamu, Dirgantara adalah langit. Kau juga sempat menggodaku, Dirgantara dan Jingga adalah padanan yang serasi. Kemudian entah karena dorongan angin atau apa, hatiku sepakat meng-iya-kan. Sejak Rabu itu, kita semakin dekat. Kau ibarat langitku, sedangkan aku laksana warnamu.
Hari ke-27 Jingga dan Dirgantara. Pukul tujuh malam ini, aku dan kau telah merancang janji perihal pertemuan kita yang kelima. Malam itu ada yang tak biasa, lunar tampak samar, sang sabit murung bagai wanita pundung, gemuruh hujan berisik pertanda hari di luar sana tengah redum. Tapi kondisi alam tak dapat menanggang ingin kita untuk bersua.
Seperti biasa, aku menunggu di pelataran Jalan Naga. Baju biru-mudaku terus dikeroyoki oleh pasukan hujan yang datang beriringan. Sepatu hitam andalanku pun mulai tenggelam dalam lubang berisi genangan. Kompas arloji menunjukkan pukul setengah delapan malam, sudah lebih setengah jam aku menunggu ditemani payung yang kau berikan.
Satu jam kemudian, Dirgantara tetap tak datang. Aku marah setengah mati. “Jangan sampai bajingan ini memintaku untuk bertemu lagi,” batinku bebal.
Pukul 22.41 aku masih terbangun, ketika cahaya ponsel memintaku untuk melirik pada sebuah pesan yang masuk.
Demi apapun mataku terbuka lebar-lebar kala itu. Nafasku sejenak berhenti, nadiku seolah tak lagi berbunyi, dan rasanya darahku tak mengalir sampai ke otak. Kaget setengah mati aku melihat sebuah pesan, "Jingga, Dirgantara mengalami kecelakaan dan sekarang di RS. Rawat Asih Jakarta."
Secepat kilat aku sampai di sana. Dengan nafas sesak dan pipi yang bersimbah air mata, serta suara yang untungnya masih tersisa, aku bertanya pada salah seorang resepsionis. "Ruangan Dirgantara Katamso di mana, Mbak?" ucapku dengan nada tak sabar. "Kak Dirgantara sudah pulang Mbak, baru saja," jawab wanita berbalut busana putih itu. Aku menghela nafas lega, setidaknya kau pasti sudah lebih baik.
Namun ternyata makna "pulang" yang kutangkap adalah keliru. Ya, kau pulang ke tangan Tuhan, meninggalkanku dengan berbagai pertanyaan.
Bendera itu berkibar tepat di halaman rumahmu. Kuning, aku benci warna itu! Tangisan dan suara pengajian menjadi irama, aku tidak becanda, aku benar-benar tak suka.
Ternyata, hujan malam itu juga punya sebuah tujuan, mengambilmu kembali untuk pulang. Kau bohong! Katanya langit dan jingga adalah dua pasang yang tak dapat ditawar lagi, nyatanya kini kau meninggalkan aku pergi.
Hujan bilang kehilangan adalah berat, maka jagalah yang dekat. Lalu mengapa jingga tetap ada, jika langit tak lagi bersisa?
























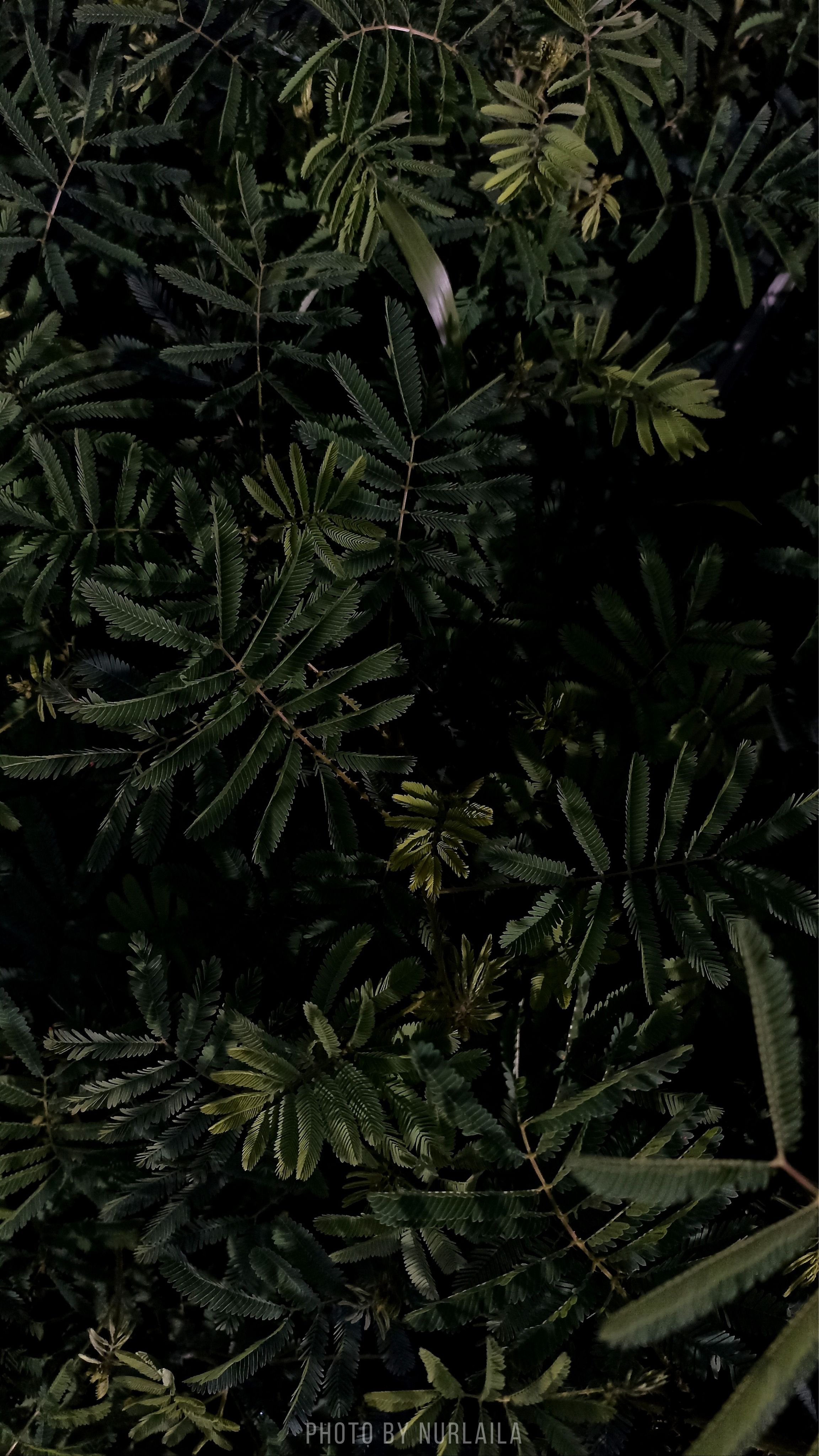








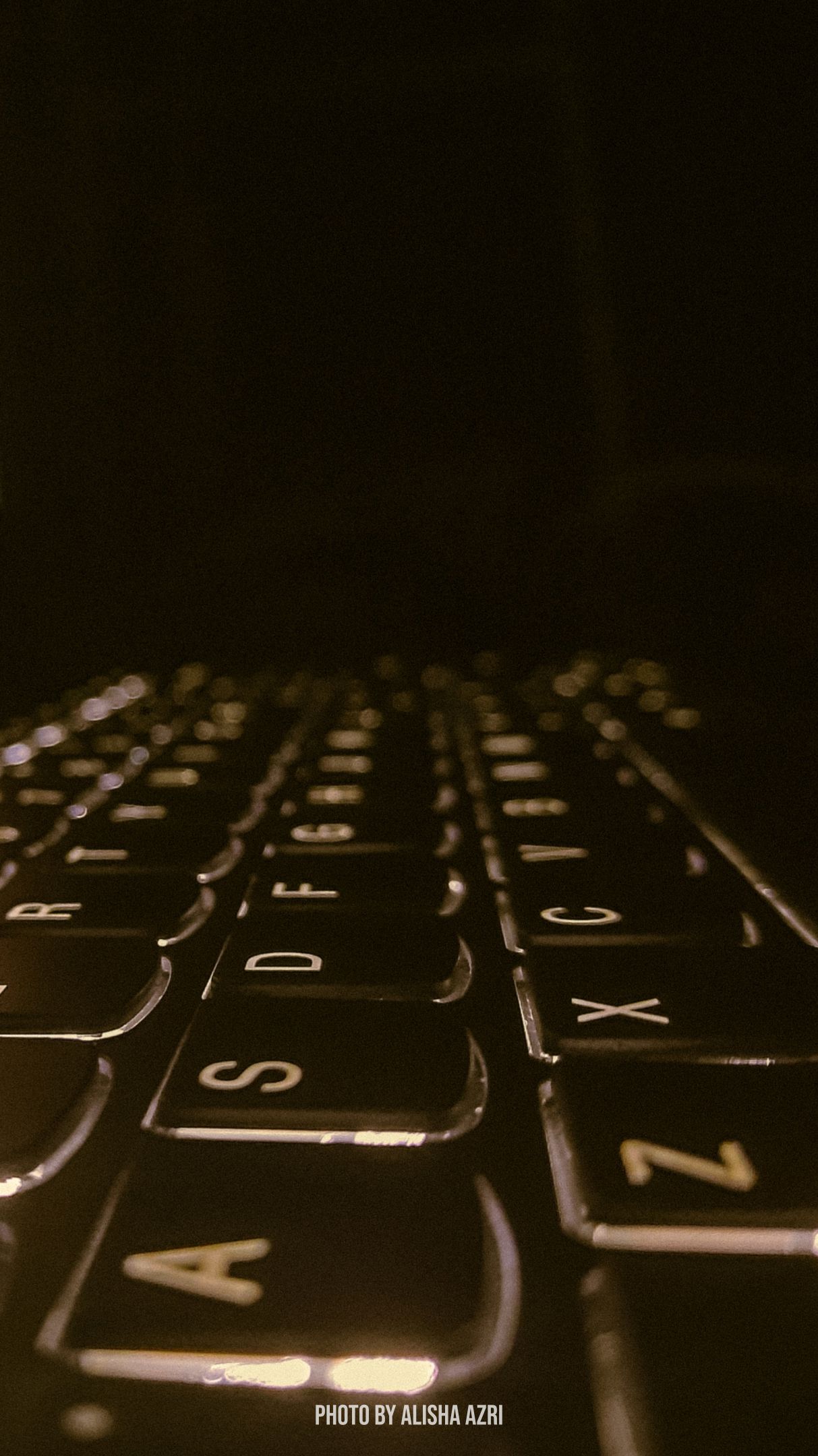












.jpg)
.jpg)